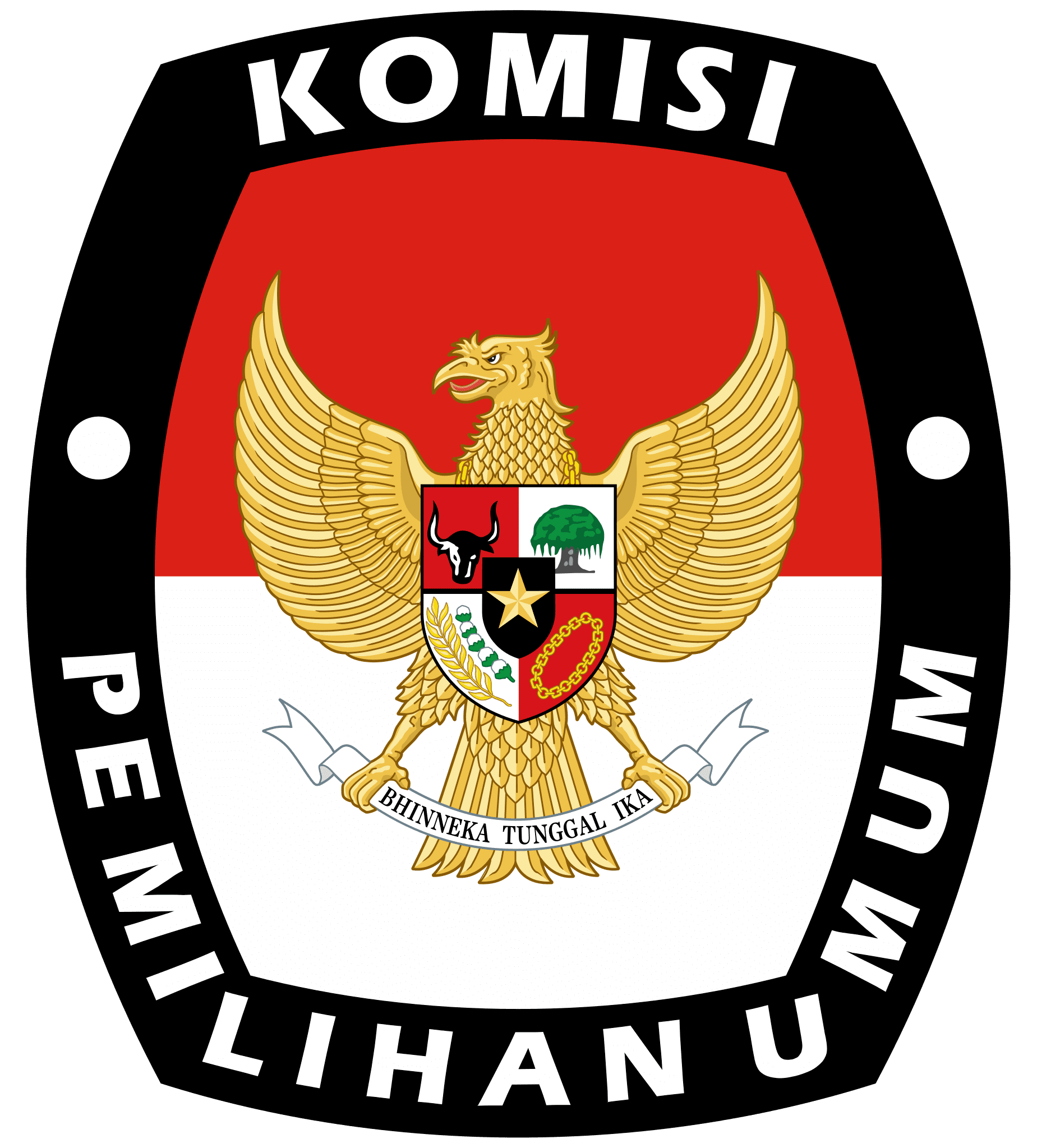Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol
Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 Oleh Shandy Akbar Kelana – Anggota KPU Kab. Tangerang DASAR HUKUM PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1076/PL.01.2-SD/06/2025 tanggal 18 Juni 2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melaluia Sipol Tahun 2025. Sesuai Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Dalam hal pemutakhiran data partai politik melalui sipol, seluruh partai politik pemilu 2024 di kabupataen Tangerang harus melaksanakan sesuai pasal 146 : Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud meliputi: kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; keanggotaan Partai Politik; dan domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan secara berkala dengan ketentuan: pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni; pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember; penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni (untuk tahun 2025 pada tanggal 26 Juni 2025); dan penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember (untuk tahun 2025 pada tanggal 29 Desember 2025). Setelah parta politik melakukan pemutakhiran data partai politik, KPU Kab. Tangerang akan melakukan verifikasi administrasi.
Selengkapnya