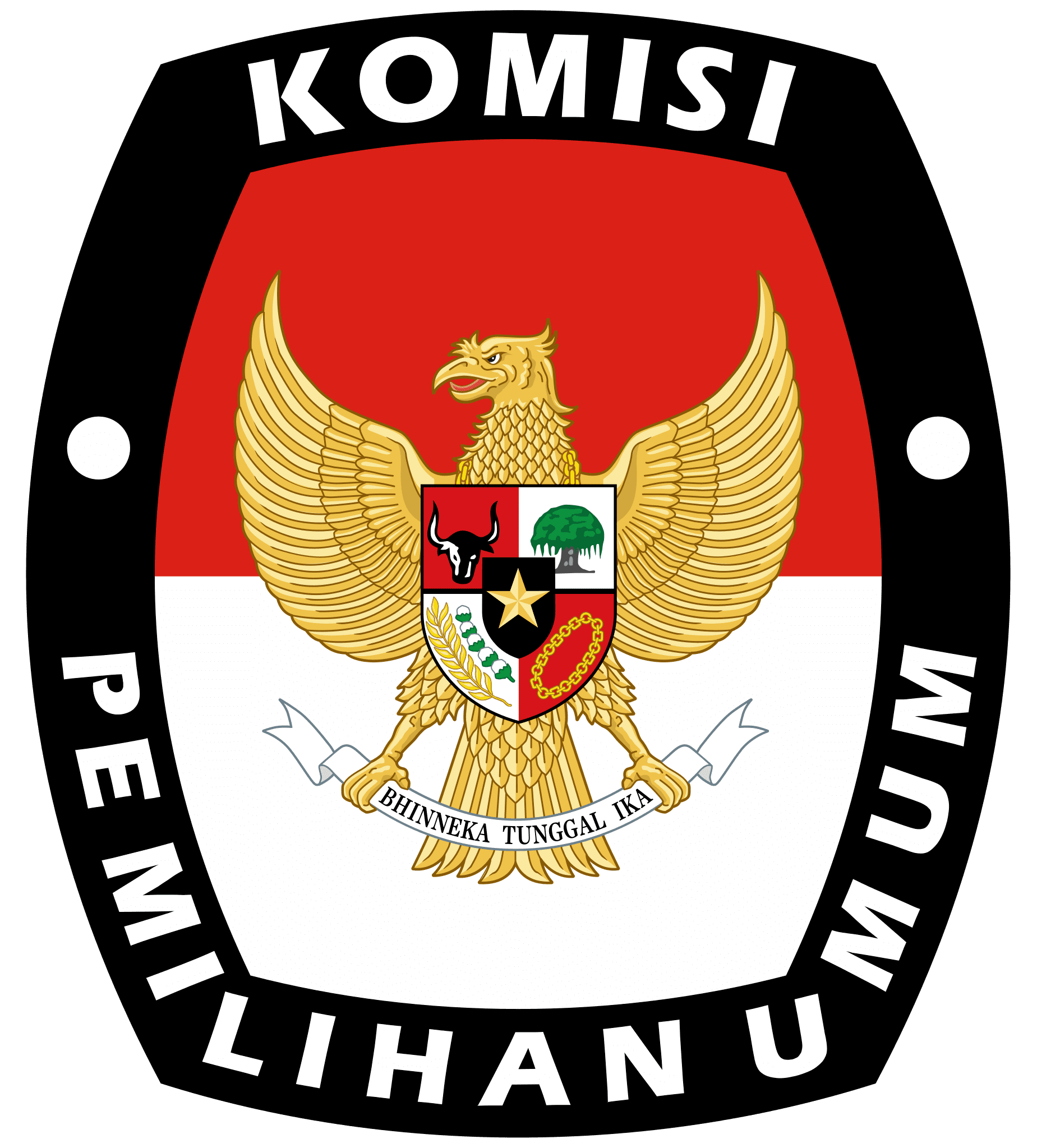Menakar Lahirnya Badan Peradilan Khusus
Menakar Lahirnya Badan Peradilan Khusus “Konstruksi Electoral Justice System dan Sejarah Penyelesaian Sengketa Pilkada di Indonesia” Oleh: Dedi Irawan Anggota KPU Kab. Tangerang Di tengah dinamika demokrasi elektoral Indonesia, kebutuhan akan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada menjadi semakin mendesak. Pemilu yang demokratis bukan hanya tentang kompetisi lima tahunan, tetapi juga tentang bagaimana negara menjamin bahwa setiap proses berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip yang sama berlaku dalam penyelenggaraan pilkada, yang meski bersifat lokal, mengandung konsekuensi politik yang tak kalah besar dari pemilu nasional. Salah satu pilar penting untuk menjamin nilai-nilai tersebut adalah keberadaan electoral justice system, suatu kerangka yang mengatur bagaimana pelanggaran pemilu dicegah, direspons, dan dipulihkan. Di sinilah perdebatan mengenai lahirnya Badan Peradilan Khusus Pemilu/Pilkada menemukan relevansinya. Elektoral yang Adil: Mengapa Kita Membutuhkan Electoral Justice System? Electoral justice system pada hakikatnya adalah sistem yang memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, hingga putusan dalam proses pemilu sesuai dengan aturan hukum serta mampu melindungi hak-hak elektoral warga negara. Sistem ini menyediakan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan, mengajukan pemeriksaan, dan mendapatkan adjudikasi yang memulihkan hak-haknya. Setidaknya terdapat tiga spektrum mekanisme yang hidup dalam sistem keadilan elektoral: Korektif/Formal, yakni mekanisme gugatan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui hasil pemilu. Punitive, yaitu pemberian sanksi administratif maupun pidana terhadap pelaku pelanggaran. Alternatif, berupa penyelesaian sengketa secara sukarela, informal, dan lebih mengedepankan mediasi. Sistem ini bukan hanya alat teknokratis, tetapi juga fondasi legitimasi politik. Tanpanya, pemilu berisiko kehilangan integritas dan kepercayaan publik. Pelajaran dari Pengalaman: Mahkamah Konstitusi dan Sengketa Pilkada Sejak kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada dialihkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga ini telah menunjukkan peran penting dalam menjaga keadilan substantif. Meskipun jadwal penyelesaian perkara yang singkat sempat menimbulkan kritik, MK membuktikan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan aritmatika suara semata. Preseden penting terlihat pada Putusan Pilkada Jawa Timur 2008. Kala itu, MK secara tegas meninggalkan label “Mahkamah Kalkulator”, karena tidak lagi hanya memeriksa angka-angka hasil perhitungan suara, tetapi menilai keseluruhan proses, bahkan memerintahkan pemungutan suara ulang di dua kabupaten. Langkah ini menandai bahwa MK menempatkan keadilan substantif di atas pendekatan kuantitatif semata. Meski demikian, muncul sebuah pertanyaan klasik: Haruskah setiap masalah yang muncul dalam sebuah lembaga dijawab dengan membentuk lembaga baru? Jawabannya tidak selalu demikian. Namun dalam konteks sengketa pilkada, problem kepastian hukum jangka panjang memang mendorong kebutuhan akan desain kelembagaan yang lebih stabil dan terlembaga. Mengapa Badan Peradilan Khusus Menjadi Relevan? Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 sesungguhnya telah menempatkan pembentuk undang-undang pada kewajiban konstitusional: membentuk badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Lembaga ini harus berada di bawah kekuasaan kehakiman, khususnya Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan oleh UUD 1945 dan UU 48/2009. Dalam desain ini, penyelesaian sengketa pilkada tidak berdiri di luar bangunan peradilan nasional, melainkan menjadi kamar khusus yang menangani perkara elektoral secara lebih teknis, konsisten, dan berkelanjutan. Hingga badan ini terbentuk, MK tetap menjalankan fungsi penyelesaian sengketa. Namun kondisi ini bersifat sementara dan tidak ideal untuk jangka panjang. Menimbang Urgensi dan Tantangannya Pertaruhan politik dalam pilkada sangat tinggi. Godaan manipulasi, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik curang adalah ancaman nyata. Karena itu, keberadaan badan peradilan khusus akan memberikan: Keberlanjutan kelembagaan, karena MK sejatinya memiliki fokus konstitusional yang lebih luas. Konsistensi yurisprudensi, karena kamar khusus dapat membangun standar penanganan perkara yang lebih teknis dan stabil. Kepastian prosedural, terutama terkait beban pembuktian, tenggat waktu, hingga standar pemeriksaan pelanggaran. Namun pembentukan lembaga baru juga mengandung risiko: potensi tumpang tindih, biaya kelembagaan, dan tantangan desain sistem yang matang. Penutup: Jalan Tengah Menuju Peradilan yang Lebih Komprehensif Gagasan pembentukan Badan Peradilan Khusus tidak boleh dipandang sebagai sekadar institusionalisasi baru. Ia harus dipahami sebagai bagian dari pembangunan ekosistem electoral justice system yang lebih kokoh, yang mampu mencegah penyimpangan, menindak pelanggaran, sekaligus memulihkan hak elektoral secara adil. Indonesia membutuhkan sistem yang tidak hanya bekerja setiap lima tahun, tetapi yang terus memastikan bahwa demokrasi tidak tergelincir oleh penyalahgunaan kekuasaan ataupun kompromi prosedural. Badan peradilan khusus dapat menjadi salah satu jawaban, asalkan dibangun dengan desain yang matang, bukan sekadar respons instan terhadap problem jangka pendek. Di titik ini, menakar lahirnya Badan Peradilan Khusus menjadi bagian dari ikhtiar besar: memastikan bahwa suara rakyat tidak hanya dihitung, tetapi juga dijaga martabat dan keadilannya.
Selengkapnya